Text
Martha and I (Chapter 7)

Baiklah, aku ingin kalian membayangkan sebuah ruangan. Gelap, dengan pengeras suara yang cempreng. Maksimal bisa diisi dengan 50 orang—tapi tidak pernah terjadi, percayalah aku sudah sering ke sini dan paling mentok separuh saja yang terisi, itupun jarang. Tempatnya punya sistem pendingin ruangan yang aneh. Kalau tiba-tiba di tengah kegiatan yang kalian lakukan udara jadi agak panas, itu artinya kalian harus cepat-cepat menyudahi apapun yang kalian lakukan—tidak banyak yang bisa dikerjakan selain duduk-duduk, karena itu tandanya si operator sedang ingin mengubah film. Slogan ‘pelanggan adalah raja’ bisa ditemukan di mana saja kecuali di sini.
Ini bioskop kesayangan Martha dan karena orang-orang seperti Martha-lah tempat semacam ini tetap bisa berdiri. Tidak perlu banyak, asal loyal. Tidak peduli lampu led pada trap yang biasanya menunjukkan nomer kursi sebagian mati, atau plafonnya yang datar sehingga membuat speaker memantul-mantulkan audio yang menggema, atau jenis ketidaknyamanan seperti ruang untuk kaki lebih sempit daripada bioskop pada umumnya, tempat ini sudah mirip ibu-ibu 50 tahun yang kebanyakan memakai susuk. Sulit ditolak sekali kau melihatnya.
Bioskop buka seperti jadwal puasa Daud. Sehari buka, sehari tutup dan hanya bisa diakses sore hari sampai tengah malam. Film yang diputar hanya dua jenis, dokumenter dan film berbahasa asing (jangan pergi ke sini pada hari Kamis, biasanya yang diputar film India. Well, aku tidak punya masalah dengan film India tapi siapa tahu kalian begitu). Sesungguhnya konsep bioskop ini unik. Setelah kita membayar tiket, tidak ada yang tahu film seperti apa yang akan ditayangkan selain Tuhan Yang Mahaesa dan pemilik bioskop. Semacam blind date, tapi ‘date’ yang bersangkutan dengan bioskop dibaca ‘death’. Bisa saja kau mendapatkan jatah film Alfred Hitchcock, film noir, film bisu, film dengan bahasa yang bahkan baru pertama kali kau dengar— film terakhir yang kutonton ternyata berbahasa Amharik, bahasa resmi Ethiopia, film erotis yang tentu saja tanpa sensor, film vampire murahan yang pertama tayang saat nenekmu masih remaja, dan favorit Martha adalah film dokumenter. Datang ke bioskop ini seperti membuka kotak Pandora.
Penjaga sekaligus pemiliknya, Pak Salamun Salam (iya, dia minta dipanggil begitu. Jangan tanya kenapa sebab aku pun tak tahu) tampak seperti relik biksu yang terlalu banyak makan lobak. Outfitnya itu-itu saja, kaos singlet dan jam tangan rantai yang keemas-emasan (atau mungkin itu emas sungguhan?). Kepalanya botak di tengah, rambut yang ada diminyaki dengan sia-sia. Kalau ia sedang mengangkat tangan, bisa dilihat bulu ketiaknya seolah mengejek kebotakan rambutnya. Ada juga pegawai bioskop bernama Rendra (ya Tuhan, percayalah dia selalu bersikeras minta dipanggil Rendra. Dari tampangnya, nama aslinya akan terdengar seperti Safi’i yang dieja Sapi’i). Dia asisten Pak Salamun Salam yang seperti raja di dinasti kecilnya ini. Selain dua orang itu, tampang petugas yang lain tidak kukenal sebab mereka terlalu sering diganti.
Aku tidak tahu bagaimana Martha menemukan tempat nyentrik di jantung metropolitan. Lupakan soal itu, fakta bahwa ada bioskop seperti ini saja sudah sangat aneh. Aku punya keyakinan yang sepenuhnya tumbuh karena kecurigaan. Gedung bioskop, yang kalau dari luar berupa ruko bergaya art deco, benar-benar sesuatu yang… apa ya, sepertinya muluk sekali kalau menyebut bioskop Pak Salamun Salam sebagai hidden gem. Tapi kalau kau punya selera nyeleneh macam Martha, kau pasti rajin ke sini.
“Pasti mereka bandar narkoba atau sindikat dagang ginjal,” kataku pada Martha yang kemudian dibalas dengan tawa berderai. Aku memukul lengannya. Ini masalah serius, seseorang tidak boleh tertawa saat mendengar perkara serius, iya kan?
Waktu itu kami berada dalam bioskop yang diisi empat kepala (lima kalau kepala Pak Salamun Salam dihitung juga dari ruang kendali). “Coba deh perhatiin, pemakaman aja masih lebih rame. Lagian mustahil dia bisa bayar sewa atau pajak bangunan, belum lagi film-film yang pasti semuanya ilegal. Tempat kayak gini kelihatan banget kalau dipake buat nutupi sesuatu. Anak kucing pun tahu kalau bisnis ini mencurigakan.”
Bioskop Pak Salamun Salam tidak melulu menyajikan film-film purba. Kalau sedang hoki kau bahkan bisa menonton film asing yang belum ada di bioskop Indonesia. Dulu aku iseng memperhatikan layar, siapa tahu ada watermark dari LK21 atau situs film ilegal lainnya. Tapi usahaku tidak membuahkan hasil.
Martha menahan ekspresi wajahnya seserius mungkin karena paham aku mencoba untuk membahas hal gawat. Jujur saja wajahnya waktu itu lebih mirip orang kebelet pipis.
“Say something!” seruku sambil menyodok rusuknya.
“Salah semua.” Ia balas berbisik. “Kecuali satu, betul banyak filmnya yang ilegal.”
Aku bertepuk tangan sekali. Girang. “I knew it!”
“Ssst! Diem,” balas Martha yang menahan tawa. “Tapi Pak Salam bukan bandar narkoboy apalagi sindikat dagang ginjal. Dasar sotoy. Kamu tahu kenapa jadwal bukanya selang-seling?”
Aku memberinya tatapan ‘apa aku terlihat tahu hal semacam itu?’
Martha dan beberapa orang VIP lainnya datang ke bioskop ini seperti jadwal scalling, dan mereka punya wewenang memanggil Pak Salamun Salam dengan Pak Salam saja (ojek pengkolan kemarin kudengar malah memanggil bapak-bapak misterius itu dengan Mister Salam. Ya ampun, apakah hanya aku yang waras di sini?).
Dia tergelak. “Karena di lantai atas, digunaain buat kasino yang bukanya saat bioskop libur. Trus untuk sistem sehari tutup sehari buka, aku pernah nanya langsung sama Pak Salam. Katanya itu sudah jadi ciri khas tempat ini sejak pertama dibangun sama buyutnya. Dan untuk bioskop, Pak Salam nggak mau repot-repot ngejelasin dari mana dia dapetin semua film-filmnya itu.”
Dalam bayanganku, kasino selalu identik dengan tempat di mana Percy dkk teler saat sedang berusaha menemukan mutiara teleportasi(?). Tempat judi yang mewah dan semua tampak berlebihan. Pengunjungnya bersolek habis-habisan, begitupula bagunannya. Tapi di sini, kasino kelihatan peyot sekali meski boleh kuakui secara keseluruhan bangunannya terawat dengan baik. Aku tidak pernah membayangkan lantai dua dan tiganya difungsikan sebagai tempat judi yang aktif.
Martha melanjutkan, usaha Pak Salamun Salam bisa tetap lancar karena ia punya cukup kuasa. Anaknya jadi orang penting dan meski tanpa bantuan itu, dia bisa meng-cover biaya suap untuk terus membuat bisnisnya tidak diganggu siapa-siapa.
“Trus kenapa kamu nggak bilang dari tadi.”
Marta kembali menatap layar dan berseloroh. “Nggak apa-apa. lucu aja ngeliat kamu kayak gitu.”
Aku bersungut-sungut dan mengikuti Martha melihat ke layar dengan film berbahasa Yunani yang sedang diputar.
***
Setelah aku menangis dan menghabiskan segelas boba, Martha membawaku ke bioskop Pak Salamun Salam. Anggap saja kalian tidak pernah mendengar pengakuanku, tapi sungguh, aku merindukan bioskop aneh dengan pengharum ruangannya yang berbau ringo ame ini.
Kami tidak melihat Rendra di mana-mana, namun ada bocah penjaga loket yang baru. Aku gatal untuk menanyakan ke mana Pak Salamun Salam, namun tidak jadi. Kami memasuki lorong seraya menenteng sekarton penuh cala lili dan gerbera. Tadi saat aku menemani Martha membeli bahan-bahan untuk memasak, toko bunga di muka pasar baru saja kedatangan stok baru. Bunga-bunga cantik harus segera dibawa pulang.
Menolak untuk meletakkan bunga di mobil karena walau sekarang sudah pukul delapan malam, suhu di dalam mobil pasti membuat mereka layu, aku membawa semuanya ke dalam bioskop. Martha menjelaskan pada bocah loket yang mungkin masih SMP bahwa tidak ada makanan yang dibawa, hanya bunga. Satu-satunya peraturan ketat dari bioskop yang cuma memiliki satu ruang teater ini adalah dilarang membawa makanan dan minuman. Sebaik apapun kau menyembunyikannya, pasti akan ketahuan. Dulu sepasang orang—karena aku tidak tahu mereka kekasih atau teman, diusir dan dilarang untuk datang minimal sebulan dari insiden itu. Tentu saja mereka tidak pernah kembali dan tentu saja Pak Salamun Salam tidak terpengaruhi akan hal itu.
“Aku masih inget gara-gara For Sama, malah ikut-ikutan demen nonton dokumenter,” kataku mengenang dokumenter tentang Aleppo yang membuat mataku sebengkak tomat. Siapapun kalian yang membaca ini, jangan pernah menonton dokumenter itu. Mengingatnya pun masih membuatku ingin menangis.
Martha tersenyum dan menyejajari langkahku. Sekarang hari Selasa, lorong bioskop, karpet empuk, aku tidak menyangka bisa berada di sini lagi bersama Martha.
Film yang akan diputar berjudul Belle Epine. Jangan tanya ceritanya bagaimana karena sewaktu lenganku digoncang pelan oleh Martha, aku terbangun dari mati suri. Aku melihat ia hanya mengenakan kaos dan kemeja flanelnya sudah jadi selimutku. Kakiku mati rasa, leherku tidak berada pada tempat yang tepat, pikiranku masih menyangkut di suatu tempat dalam mimpi yang tidak bisa kuingat jelas, Martha memapahku keluar dari bioskop seperti mengantarkan nenek-nenek kukang dan menyapa sambil tertawa pada Pak Salamun Salam yang duduk-duduk di dalam loket. Bocah tadi sudah menghilang, jam dinding di lobi memberitahuku kira-kira sejam setengah kulalui dengan tidur paling nyenyak sejak—entahlah sejak kapan.
“You can sleep over if you want,” tawarku setelah ia memarkirkan mobilku.
“Aku bisa pulang naik gojek.”
“Kamu perempuan, sekarang udah jam 10 lebih. Dan besok kita kuliah agak sore.”
Ia melepaskan sabuk pengaman dan tampak berpikir lalu mengangguk. Kami naik ke lantai enam dengan kantong belanjaan.
“Kamu laper, nggak?” tanya Martha.
“Aku ngantuk, tapi karena kamu ngomong gitu aku jadi inget belum makan apa-apa.”
“How about some spaghetti before bed?”
“Hell yeah!” teriakku di dalam lift.
Terima kasih Tuhan, telah mengembalikan pertemanan ini, ucapku dalam hati yang kemudian ditimpali oleh diriku sendiri dengan, emangnya kamu sama Martha temenan? I mean, ‘cuma’ itu? Yakin? Dibalas lagi oleh, kan emang temen. Apa lagi?
Temen itu kayak kamu sama Mindy, atau Elias, atau Aminda, atau siapapun yang nggak bikin kamu linglung.
Lah, kok lawak. Martha kan emang—
Kamu tahu ini ngerujuk sama apa…
Tunggu dulu, dari mana datangnya suara-suara ini?
“Kamu mau tidur di lift?” tanya Martha. Berdiri di bagian luar lift.
Sudah berapa lama aku melamun?
2 notes
·
View notes
Text
Martha and I (Chapter 6)

Hebat benar aku tidak menjerit. Tapi suaraku tersangkut di pangkal tenggorokan. Dan begini ekspresi Martha: 😐. Dia melihatku seperti melihat orang biasa—ya, memang maunya aku dilihat bagaimana? Mungkin aku sedikit berharap ia juga sama kagetnya sepertiku karena ini baru pertama kalinya sejak momen di kamar Martha, kami bersitatap dalam jarak yang dekat.
Toilet masih dipenuhi perempuan-perempuan yang berisik. Aku hampir oleng dan menabrak salah satu dari mereka. Namun cepat-cepat aku melipir ke wastafel dan mencuci tangan. Penguasaan diri yang cukup bagus, Lunar, bisikku. Oh, tidak sebagus itu saat kudengar Martha berucap dari belakang:
“I’m sorry if I’m terrified you.”
Ha? Apa katanya?
Aku tetap menggosok tangan sampai rasanya tanganku hilang di dalam gelembung sabun.
“Na, I’m sorry that I—“
“I know, I know. I get it. Yes you are terrifying me. Puas? Sekarang aku mau cuci tangan sampe bersih jadi kasih aku waktu untuk itu.” Oh tidak, bukan seperti itu maksudku, Mar.
“Oke, I’ll wait then.” Dari pantulan cermin, Martha menyilangkan tangan di depan dada.
Aku berbalik menghadapnya. “Wait, what? Apa yang mau kamu tunggu? Tbh, I don’t need this conversation.” NO, I NEED THIS.
“Oh yes, you need this,” balasnya.
Baiklah, terima kasih sudah memahamiku. “No I’m not. I’m so not.”
“Oke berarti aku yang butuh. Maaf kalau waktu itu aku bikin kamu… takut? Idk.”
“Hm? Kapan? Yang barusan aku maksud itu, kamu tiba-tiba berdiri di depan toiletku dan bikin aku kaget. What are you doing? It’s creepy.”
“Na, semuanya penuh. Lagian aku nggak tahu kalau kamu ada di situ.”
“Ya, kenapa nggak nunggu di bilik yang lain?”
“Jangan berputar-putar, deh. Aku di sini cuma pengin ngelurusin, aku nggak bermaksud bikin kamu takut sama pengakuan soal… kamu tahu soal apa. Aku kira kita sudah cukup dekat jadinya aku bisa ngasih tahu—”
“Bukan! Aku kan sudah bilang aku kaget sama kamu barusan. Bukan masalah, ya Tuhan aku bahkan nggak mau bahas ini, oke? Aku cuma butuh cuci tangan. Itu aja. Kamu ngerti nggak sih?!” Sekarang aku nyaris berteriak dan gerombolan di toilet mengerling ke arah kami berdua. Rupanya mereka menemukan tontonan lebih menarik dibanding gosip yang dari tadi mereka perbincangkan. “Just. Wait. For. Me. outside, oke?” kataku pada akhirnya dengan suara yang kuusahakan sekalem mungkin.
Martha mengangguk dan berlalu. Gerombolan berdeham dan satu per satu berjejer di wastafel. Merapikan rambut, memupuri kembali wajah mereka, dan cuci tangan sama sepertiku—tidak, mereka tidak seberingas aku. Ngomong-ngomog, parfum mereka membuatku pusing.
Setelah mengeringkan tangan dan mempersiapkan diri, aku keluar dari toilet. Sebuah tangan menarikku tepat saat langkah kakiku menyentuh bagian luar toilet.
Dingin. Tangan Martha dingin dan ia mencengkram pergelanganku dengan erat, terlalu erat dari yang semestinya. Di sebuah bangku taman, ia akhirnya melepaskanku.
“I’m sorry…,” desahnya.
Aku tidak berani melihat ke arahnya.
“This is not your fault.” Suaraku bergetar dan emosi yang telah lama mengangguku tumpah begitu saja. Andai emosi yang kita keluarkan memiliki wujud. Pasti aku sudah tenggelam karenanya. Kupandangi semut-semut yang membawa daun di bawah kakiku. Pada titik itu aku tidak tahu, mana yang lebih gemetar, suara atau bahuku.
Untuk menghentikan tangis, ada baiknya untuk mulai memikirkan hal lain. Maka aku mengingat rasa air mata yang asin. Pantas saja setelah lama menangis, seseorang akan kehausan. Banyaknya kadar garam yang–
Pikiranku belum benar-benar sibuk ketika Martha membawaku ke dalam pelukannya dan berkali-kali mengucapkan mantra ‘that’s okay, everything gonna be okay’. Aku jarang percaya ucapan klise semacam itu. Tapi Martha membuatnya terdengar sangat apa adanya sehingga mustahil aku menolaknya.
Kenapa saat sudah besar sekalipun, kita masih bisa nangis sampai sesenggukan?
2 notes
·
View notes
Text
Martha and I (Chapter 5)
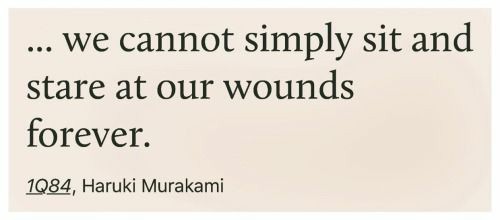
Kalau otak orang depresi dibedah, kira-kira bentuknya akan sama dengan orang normal atau tidak ya? Apakah otak mereka akan lebih berminyak, penuh noda, bopeng, kisut? Seperti visualisasi paru-paru perokok. Aku punya sedikit cerita menyedihkan (dan agak menyeramkan). Adik mama depresi karena musabab yang sampai sekarang tidak kuketahui. Semua orang, nampaknya, menyembunyikan cerita itu rapat-rapat. Tante Adelin dalam ingatan diniku, sangat… melar. Dagunya ada dua dan dia selalu kesusahan bernapas sambil dibanjiri keringat yang sampai-sampai membuatku percaya pasti mama bersaudara dengan dispenser. Tepat ketika aku kelas 5 SD—kalau memoriku bisa dipercaya, Tante Adelin ‘menyusut’. Fitur wajahnya mulai menampakkan kemiripan dengan punya mama. Alih-alih termenung terus, dia jadi lebih ceria. Suaranya tambah jernih. Apa mungkin dua orang hidup dalam satu kulit yang sama? Dan pada masa-masa tertentu, kalau sudah lelah dengan tampang yang satu, mereka dengan mudah berganti kulit. Seperti ular? Dunia orang dewasa sungguh aneh, pikirku waktu itu.
Baru setelah aku cukup besar dan pertanyaanku cukup penting untuk dijawab sungguh-sungguh, aku mendapat kesempatan itu. Kutanyakan apa yang terjadi pada Tante Adelin waktu itu. Beruntung, ia mau menanggapi dengan berbesar hati. Katanya sempat ada sesuatu di masa lalu dan Tante Adelin butuh pertolongan. Sayang sekali penolongnya waktu itu malah balik menyerang tubuhnya.
“Tante dulu kecanduan obat, Sayang,” mulainya sambil mengusap rambutku. Ia depresi parah. Dokter yang menanganinya memberi resep untuk membantu menaikkan serotonin di otaknya. Waktu itu ilmu psikiatri belum berkembang seperti sekarang. Semua hal bisa diselesaikan dengan pendekatan medis dan hanya melalui obat-obatan. Aku sempat menggali lebih dalam soal masalah Tante Adelin. Ternyata sebelum riset yang dilakukan seorang dokter Inggris bernama Irving Kirsch dan muridnya Guy Sapirstein, depresi selalu dipahami sebagai malfungsi dalam otak. Kemungkinan seperti depresi juga disebabkan oleh lingkungan sekitar belum masuk hitungan.
“Dengan bantuan SSRI, tante memang sempet baikan. Tapi semakin sering mengonsumsi obat itu, tubuh tante jadi resisten dan butuh dosis yang lebih tinggi. Dari 20 mili, menjadi 30, lalu 40, tahu-tahu sudah 60 mili. Dua pil biru tante minum setiap hari,” kenangnya. Meski sudah rutin mengonsumsi obat, tanda-tanda depresi tidak 100% berhenti. Itu alasan lain mengapa dosisnya terus bertambah. Logikanya, untuk membunuh monster yang besar, diperlukan amunisi yang berat juga. Ketakutan bahwa obat tak lagi dapat membantunya membuat Tante Adelin lebih cemas daripada sebelumnya. “Bukannya sembuh, karena efek samping obat, tante malah tambah depresi.” Tante Adelin melanjutkan sambil tersenyum mafhum.
Aku memeluknya, terlambat sadar bahwa keputusanku untuk meminta Tante Adelin bercerita ternyata sangat tidak bijak. Sambil balas merengkuhku, ia berkata bahwa itu tidak masalah. Sebab sekarang ia sudah lebih kuat dibanding penderitaannya kala itu.
Apakah aku sedang depresi? Itu pertanyaan kedua setelah masalah otak tadi. Kekhawatiran akan menjadi Tante Adelin the Second lebih menuntut banyak perhatian dibanding pertimbangan apakah aku depresi atau tidak. Maka seperti orang dewasa yang tahu caranya membersihkan masalahnya sendiri, aku membuat janji temu dengan psikolog. Ternyata tidak terlalu buruk. Ini yang kemudian aku simpulkan dari beberapa sesi konseling yang kulakukan:
1. Benar, renggangnya hubunganku dengan Martha memicu insomnia akut (ini pertanyaan ketiga, kalau dibedah akan lebih buruk mana, otak orang depresi atau otak orang yang punya gangguan tidur? Aku mulai menandai perubahan yang kurasakan sejak masalah sialan ini ada. lebih gampang hilang konsentrasi (aku lupa menarik kunci mobil setelah menguncinya dan ini tidak terjadi sekali), lemot luar biasa lelah meski hanya untuk memikirkan berapa jumlah kembalian, emosiku lebih kacau dibanding bayi yang sedang tantrum.
2. Satu-satunya yang kubutuhkan adalah resolusi dengan diriku sendiri. Kemudian dengan Martha. Dua hal yang lantas terlalu muluk untuk dilakukan.
3. Sakit mental memang benar-benar bisa berimbas pada sakit fisik.
4. Dengan sadar aku mengakui banyak hal yang kututupi dari psikologku. Masalahku tidak datang hanya karena aku tiba-tiba bermusuhan (oh, benarkah aku sedang bermusuhan?) dengan Martha. Lebih dari itu. Besar kemungkinan aku sedang dalam penyangkalan demi penyangkalan tentang siapa aku sebenarnya. Tentang orientasi seksualku. Aku merasa seperti bawang yang salah dipupuk. Jadi saat dipanen, tubuhku terlalu banyak menyimpan lapisan. Meyimpan rahasia. Poin kelima ini kusimpan rapat-rapat tapi baunya pasti tercium. Bagaimanapun aku seorang bawang. Ada perjanjian tidak tertulis antara aku dengan psikologku. Selagi ia bertanya, ‘apa ada yang lain? yang mau kamu ceritain?’. Rasanya seperti ada yang menempelkan bara api di dekat wajahku. Kebohongan akan semakin sulit disembunyikan saat kau yakin lawan bicaramu tahu kalau kau begitu. ‘Hanya itu,’ jawabku. Lalu aku tersenyum seolah benar-benar hanya itu yang ada dalam otakku.
***
Martha meluruskan rambut keritingnya. Aku merasa patah hati seperti orang bodoh. Dari semua fitur ke-Martha-an, yang paling kusuka darinya adalah rambut. Tidak bisa kuingat berapa kali kukatakan secara langsung bahwa ia bukan Martha tanpa signature look-nya itu. Ia biasanya akan tersenyum sambil menggelengkan kepala. Tidak berkomentar balik yang sangat jarang dilakukan kalau aku sudah menggodanya. Tapi lihat sekarang manusia itu, lurus rambutnya membuatku sukar menerima kalau dia orang yang aku kenal, apalagi dengan potongan super pendek yang semakin dilihat semakin mirip Amy Dunne. Sosiopat dalam Gone Girl. Sepertinya otakku benar-benar bermasalah. Bagaimana mungkin penampilan seseorang membuatku merasa seperti ini? Oh, tunggu dulu, sepertinya hatiku lebih baik dipertanyakan daripada otakku. Kira-kira kalau orang mengalami patah hati, lebih dulu otak atau hati yang yang merespon? Aku penasaran.
Tuhan membagi-bagikan kata rupawan kepada ciptaan-Nya dengan cara yang aneh. Martha cantik, itu sudah pasti. Tapi saat kau melihatnya, wajah kecilnya, dan hidung bangirnya, kau perlu menoleh untuk kembali memastikan. Benarkah yang barusan kau lihat adalah perempuan cantik atau bukan. Martha, dengan segala keraguan yang ia bawa, memancar keluar dari lapisan bajunya. Kehadirannya ambigu. Kalau ia duduk di dekatmu, sulit untuk memastikan apakah orang ini baik atau sebaliknya, apakah ia sopan atau sebaliknya, ataukah ia ramah dan tentu saja sebaliknya.
Barusan ia masuk ke kelas dengan Irna—atau siapalah itu, mereka berbicara seru sekali. Aku yang duduk di baris belakang jadi merasa… aku bahkan tidak tahu apa yang kurasakan. Intinya rambut lurus Martha seolah mengejekku ‘Hei, lihat, aku sudah melupakanmu’.
Saat perkuliahan berakhir kurang dari 15 menit, aku izin ke toilet dan tentu saja tidak punya niatan untuk kembali.
Aku berdiam di atas dudukan kloset dan mulai memikirkan kenapa kloset di Indonesia dan kloset dengan ‘c’ di luar negeri bisa sangat jomplang sekali artinya. Kapan semester baru dimulai? Aku ingin secepatnya mengganti jadwal kuliahku. Oh Tuhan, apakah ini waktunya aku benar-benar akan seperti Tante Adelin? Tapi rasanya sungguh konyol aku bisa seperti ini hanya karena satu orang. Hanya satu orang yang akupun tak benar-benar mengerti permasalahan kami ada di mana. Apakah ini semua dariku? Tapi kenapa Martha juga bersikap seperti itu? Kalau dipikir-pikir lagi perkataanku waktu itu tidak salah-salah amat. Jangan-jangan di sini yang terlalu sensitif malah dia.
Aku memperhatikan tegel toilet yang benar-benar bersih. Aku tiba-tiba merasa sangat berterima kasih kepada tugas kebersihan. Bagaimana cara mereka terus menjaga tempat paling kotor jadi sebersih ini? Bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi ini bukan toilet mahasiswa satu-satunya, apakah yang mengurus semua toilet di gedung barat ini orang-orang yang sama? Aku percaya sebentar lagi akan benar-benar gila karena terlalu lama berkontemplasi di dalam toilet, saat segerombolan perempuan yang menggosipkan sesuatu tiba dan membuyarkan pikiran kacauku. Sepertinya aku terlalu lama duduk di sini. Maka aku pun menarik napas dan menguatkan diri. Seperti mendapat epiphany, aku memutuskan untuk merombak ulang pikiranku. Masalah tentang Martha tidak akan selesai kalau bukan dariku sendiri yang memutuskannya untuk selesai. Kalau kata psikologku, ada dua pe er yang harus kukerjakan, maka aku memutuskan untuk meringkas tugasku jadi satu. Aku tidak perlu membuat closure dengan Martha. Ini masalahku, ini urusanku. Semuanya bisa diatasi kalau aku cukup berani dan percaya diri. Tahan… semester ini saatnya aku memusingkan hal lain. Aku pasti bisa, kesibukanku pasti menolongku.
Kemudian aku keluar dari bilik toilet dengan senyum yang dikulum. Tidak pernah merasa sebugar dan sepositif ini sebelumnya. Aku pasti bisa. Harus.
Coba tebak siapa yang berdiri di depan bilik toiletku, ya, betul Amy Dunne KW super dengan matanya yang tidak terbaca.
Sudah kuduga, merenung di dalam toilet bukan ide yang bagus.
2 notes
·
View notes
Text
Martha and I (Chapter 4)

Rasanya jadi sedikit sepi setelah aku puasa bicara dengan Martha. Bayangkan saja, nyaris 24/7 keseharianku selalu dijejali dengannya. Dari roomchat, beli makan, di kampus, grocery shopping, belajar, bahkan sebelum Martha pindah kosan, dia sering menginap di tempatku karena organisasi yang ia ikuti menuntutnya untuk melanggar jam malam. Dia punya hubungan yang buruk dengan ibu kosnya. Ngomong-ngomong aku tidak pernah seintens ini dalam berteman.
Memang betul setiap hari aku masih berpapasan dengannya di ruang kelas (jadwal KRS kami nyaris 90% sama) dan di seluruh penjuru kampus, tapi kami tidak saling bertegur sapa lalu apa? Tidak ada gunanya kan? Maka aku mengubah jadwalku. Datang paling akhir—aku jadi sering terlambat, supaya tidak perlu repot-repot memindai ruangan dan mencari tempat duduk terjauh dari Martha. Konyol sekali memang. tapi pernahkah kalian begitu ingin menghindari seseorang hingga kelelahan sendiri? Aku pernah, sekarang aku mengalaminya. Bagaimana dengan Martha? Apakah dia juga menghindariku? Tentu saja, dia nyaris seperti cermin.
Suatu malam saat semuanya jadi tak tertahankan, aku menulis uneg-unegku dalam sebuah surat panjang yang kira-kira begini bunyinya:
My dearest Martha,
Maafkan aku karena waktu itu aku tidak lebih baik dari para homophobic. Aku lupa kalau perkiraan manusia bisa salah karena masing-masing dari kita berbeda. Perkiraan dibuat hanya untuk membantu kita memahami sesuatu, bukan untuk menetukan kebenaran yang mutlak. Maafkan aku. Mungkin surat ini juga untuk memberimu penjelasan mengapa aku tiba-tiba menggambar jarak yang lebar diantara kita. Aku perlu waktu berpikir. Mungkin akan banyak sekali waktu yang kubutuhkan. Dan tanpa berharap sekalipun, aku yakin kamu akan mengerti. Kamu selalu mengerti.
Tidak kupermasalahkan sama sekali kalau kamu tertarik dengan perempuan—asal tetap manusia dan bukan simpanse, aku akan menerima semua itu. Sungguh. Dan bukan cuma sekali temanku mengaku soal orientasi mereka di depanku, seharusnya aku tidak kaget saat kamu pun begitu.
Martha, aku menyukai persahabatan kita. Meski Mindy dan teman-temanku tidak setuju dengan itu. Well, jujur saja mereka melarangku bergaul denganmu. Maka aku katakan, ‘persetan dengan kalian’ yang tentunya kusampaikan dengan kemasan manis supaya mereka tidak memusuhiku. Mereka teman yang baik tapi seringnya obrolan mereka dangkal. Mereka selalu membahas hal remeh dan membuatku berpikir kehidupan hanya komidi putar, tempat anak kecil naik ke atas kuda bohongan, dalam perjalanan bohongan, dan lampu-lampu yang terlalu terang bahkan untuk ngengat sekalipun. Aku tidak menyalahkan hal itu. Mungkin realitaku saja yang lebih mirip Kuda Troya dibanding punya mereka.
Maka aku mulai mimikri untuk diterima. Aku mempelajari cara mereka berbicara, nada tertentu yang mereka pakai untuk merespon sesuatu, pekikan mereka saat melihat thrist trap, cebikan saat menanggapi orang asing dengan selera berpakaian yang buruk dsb. Bahkan kutiru juga cara mereka berpikir. Semuanya hanya untuk validasi. Aku hanya tidak tahan membayangkan diriku sendirian tanpa kawananku. Selalu kulihat orang penyendiri dengan rasa kasihan yang tak perlu. Bagaimana kalau ada orang yang berpikiran sama sepertiku? Aku tidak ingin dikasihani. Aku harus belajar menjadi cetakan Mindy dan yang lain supaya tetap disukai dan mendapatkan tempat. Sempat aku mengira semua orang sepertiku, hidup dalam dunia yang tak jujur. Apalagi dunia kuliahan yang kau mengerti sendiri bagaimana keadaannya.
Lalu kamu datang ke hidupku. Seorang teman dan pendengar. Seseorang yang jalan hidupnya jauh lebih rumit dan tidak terperi. Sehingga pemahaman yang kemudian kamu berikan terasa ganjil tapi akrab dalam waktu bersamaan. Hanya orang tuli yang dapat memahami dunia yang nirsuara. Hanya orang yang sama-sama pernah jatuh dari sepeda yang dapat sepenuhnya memahami luka, rasa malu, dan pegal-pegal setelahnya. Aku merasa dimengerti dan tidak lagi kesepian bukan hanya karena kesabaranmu dalam mendengarkan, lebih dari itu. Aku merasa dimengerti karena kamu, dengan cara yang berbeda, pernah mencicipi kehidupan yang jauh dari komidi putar. Kamu tahu rasanya menjalani hidup yang memuakkan sambil terus berseru pada diri sendiri, ‘bangkit! Kamu punya tanggung jawab atas kehidupan ini!’. Aku merasa ditemani dalam penderitaan yang senyap. Egoiskah aku jika merasa begitu?
Lucu saat aku mengatakan ini, tapi kamu membantuku menjadi diriku sendiri. Aku tidak lagi mengenal kata takut untuk mengutarakan apa yang ingin aku katakan. Tidak lagi ragu untuk melakukan apa yang harus aku lakukan. Bahkan tidak lagi plin-plan untuk memakai apapun yang membuatku nyaman. Mindy bilang kau mengubahku. Ah, andai dia tahu siapa yang mengubah siapa…
Martha, aku selalu menyukai laki-laki (atau begitulah yang selama ini coba kupercaya). Pun pandanganku terhadap sebuah hubungan sangat mendasar seperti halnya semua orang yang kukenal. Romansa dan hasrat seksual adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Hingga pembahasan AroAce-mu waktu itu membuatku merenung. Aku mulai mempertanyakan caraku berpikir. Ternyata memang benar, sebuah ikatan dan kebutuhan akan afeksi berbeda dengan ketertarikan seksual.
Sudahkah aku bercerita tentang Vina? Kami bersahabat sejak SMP-SMA. Tapi kami kembali menjadi orang asing saat suatu malam, setelah acara pensi usai dan kami bergandengan tangan menuju tempat parkir, aku mulai tersadar ada sesuatu yang ‘lain’ ketika aku berteman dengan perempuan. Bukan masalah pada orangnya, tapi ada pada cara hubungan itu terjalin. Aku bahkan terlalu takut untuk mengakuinya, namun perasaan semacam itu seharusnya tidak ada dalam persahabatan. Entah itu persahabatan dengan laki-laki apalagi perempuan. Aku sangat malu pada diriku sendiri. Rasa malu yang kemudian menjadi amarah. Vina, yang mungkin tidak tahu apa-apa, harus menanggung kekalutanku. Kuucapkan padanya, “kayaknya kita nggak bisa lagi temenan.” Awalnya dia tertawa, mengiraku sedang berkelakar. Akan tetapi sepintas kemudian ia memperhatikan kesungguhan di mataku, bibirnya mulai berkata tanpa suara, ‘what’s wrong?’ Aku yang tolol hanya bisa bergeming. Yang terjadi berikutnya aku meninggalkan Vina di parkiran yang mulai satu-satu mobil dan sepeda motor berlalu pergi. Aku naik ke Uber dan sempat menoleh ke belakang. Vina masih dengan kebingungannya, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku melihat sesuatu yang pecah dan sebuah kebenaran. Juga satu pertanyaan, ‘mungkinkah Vina merasakannya juga?’
Waktu itu saat kamu mengakui keadaanmu, aku hampir percaya sedang déjà vu. Pengakuanmu terasa seperti godam yang menghantamku. Bukankah penjelasan semacam itu yang harus kuberikan pada Vina kala itu? Bukan malah meninggalkannya sendiri… tapi aku ketakutan, Mar. Aku tahu harga dari kejujuran sejenis itu luar biasa mahalnya dan aku tidak sanggup untuk membayarnya.
Seharusnya aku tidak sekaget ini saat pengakuanmu itu akhirnya terucap. Sebab akupun tak jauh berbeda denganmu. Hanya saja aku terlalu munafik untuk berterus terang.
Apa kabar, Mar? aku menghabiskan berminggu-minggu lamanya memikirkan akan kehilanganmu sama seperti caraku mencampakkan Vina.
Salam sayang, Lunar.
Setelah kubaca ulang, aku menekan tombol backspace sampai lembarnya jadi putih bersih dengan spasi yang berkedip-kedip. Aku menutup laptop lalu bergelung di atas kasur sembari menangis sampai kepalaku mau pecah.
2 notes
·
View notes
Text
Martha and I (Chapter 3)
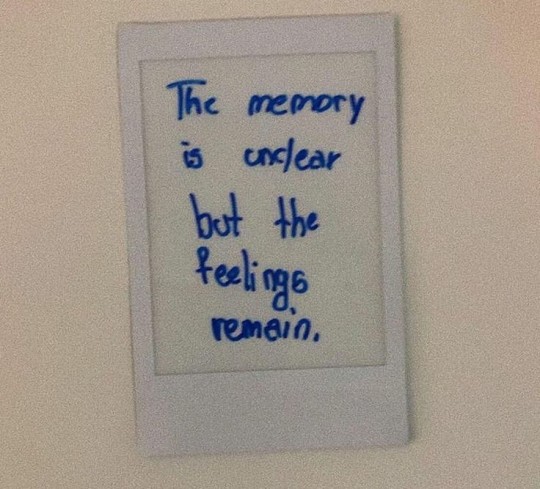
“Menurut kamu… penyimpangan itu gimana?”
Ubin yang dingin tempat kami merebahkan diri terasa keras dan lengket. Keringat sudah berhenti mengalir tapi sepertinya pori-poriku tidak mau menutup. Bisa kurasakan Martha memandang ke arah yang sama denganku. Satu bagian tembok yang belum dicat. Hampir setengah hari kami melakukan kerja kuli ini. Dia baru saja pindah kos dan kamar yang tampaknya dulu dihuni orang yang punya masalah serius dengan warna pink, sedang berusaha kami warnai ulang. Harganya bagus untuk ukuran kos yang dekat dengan kampus. Sayangnya di sekitar kosan penuh dengan pohon sengon yang demi Tuhan bisa-bisanya ada yang menanam sengon di tengah kota! Mungkin sedikit baik untuk paru-paru bertetangga dengan pohon-pohon kurus ini tapi kalau malam tiba, aku tidak mau membayangkan.
Aku sudah tidak ingat berapa kaleng cat yang dibutuhkan untuk menutup cat pink sialan di tembok, tapi tanganku dipenuhi cat Dulux putih gading. Anehnya punya Martha tidak. Bagaimana caranya melakukan semua hal dengan rapi?
“Penyimpangan itu sesuatu yang menyimpang,” jawabku.
Martha tertawa di sampingku. “Iya, trus?”
“Ya… menyimpang. Namanya menyimpang ya menyimpang. Ini ngomong apa sih? Pusing. Kasih konteks dong.”
Dia kembali tergelak. Sepertinya ini hari baik untuknya saat semalam ia uring-uringan setelah bertengkar dengan ibunya. Oh, tidak usah heran. Dia tidak pernah tidak adu mulut. Aku mulai berpikir begitulah cara berkomunikasi di keluarga Martha.
“Kenapa kalau kita suka sama sesama jenis disebut penyimpangan?” jelasnya.
“Kamu mau jawaban kayak gimana? Dari agama apa society?”
Suara tinggi Bon Iver jadi latar belakang. Aku mulai lapar. Sekantong Lays dan hampir setengah galon air yang kami habiskan tidak bisa mengganjal apa-apa. Harus kuakui kadang Martha lupa kalau temannya butuh makanan yang sedikit berat disamping keripik kentang yang ceking dan kebanyakan perasa. Oh, bayangkan sepiring nasi padang setelah kerja kuli ini selesai.
Martha menyalakan vapenya. Ia suka sekali dengan perisa kopi.
“Dua-duanya, but make it simple.” Asap berputar-putar di wajahnya.
Aku bangkit dan meninggalkan bekas di lantai. Setelah urusan memermak kamar baru Martha selesai, aku akan mandi. Mandi yang sangat lama sampai kulitku keriput.
“Oke, berhubung Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, dan Al-Qur’an kitabku… jawabannya klasik. Karena doktrin. Sejak awal Tuhan ngasih ketentuan ya laki-laki harus sama perempuan. Dan berhubung kita hidup dalam masyarakat beragama, khususnya agama samawi—karena toh bukan cuma dalam Islam yang kayak gini, akhirnya kita ngikut. So that was it.”
Martha mengeluarkan asap yang panjang dan dalam. Aku mulai berpikir dia keturunan naga bonar.
“Dan kenapa Tuhan ngasih perasaan suka sama orang yang jelas-jelas sesama jenis? Padahal katanya rasa ketertarikan itu fitrah manusia. Sesuatu yang ada bersama kita sejak orok.” Ia menahan bobot tubuhnya dengan siku kanan. Tersenyum mengejek ke arahku dengan manik mata yang menuntut penjelasan.
Aku mencondongkan tubuh ke arahnya. Menantang. “Dunia ini taman bermain Tuhan, Mar. Dia bebas mau kayak gimanain kreasi-Nya. Sama misalnya kalau kamu mangaka atau penulis. Coba tanya sama Isayama-sensei deh jelasnya. Untuk keseimbangan, harus ada komedi dan tragedi. Bayangin kalau nggak ada dua hal itu. Dunia bakal membosankan sekali.” Aku meraih kantong Lays dan mengumpulkan remah-remah di dalamnya. “Tapi kalau kamu nanya hal itu sama orang beragama tulen, malah pertanyaanmu yang bakal disleding.”
Martha terus merokok (vape masih masuk hitungan rokok elektrik kan?). “Elaborate…” selorohnya.
“Kamu nanya kenapa Tuhan ngasih perasaan kayak gitu, right? Tapi gimana kalau bukan Tuhan yang ngasih, tapi kamu yang bikin? Oke, aku tahu semua hal terjadi atas izin-Nya. Tapi Dia kan ngasih kita kebebasan juga. Kita dikasih sedikit kuasa atas hidup kita. Sedikit aja. Dan kuasa yang sedikit itu balik lagi, semua kepunyaan-Nya. Ujung-ujungnya kita harus bertanggung jawab atas pinjaman yang Dia kasih. Makanya ada sistem reward and punishment. Kalau kamu taat dan hidup sesuai perintah-Nya, surga balasannya. Tapi kalau kamu rebel, ya selamat datang di neraka. Kira-kira begitu.”
Dia membenarkan posisinya yang semula rebahan separuh, kini duduk dengan pose lotus. “Masuk akal, tapi aku ada satu lagi pertanyaan.”
“Ah, kamu mah nanya-nanya mulu.” Aku cemberut. Dia berdecak geli.
“Dengerin dulu, gimana kamu tahu kalau perasaan itu kita yg bikin kalau untuk kasus jatuh cinta hetero sekalipun, kita nggak bisa ngasih perkiraan. Orang-orang jatuh cinta setiap hati, entah itu sama temen yang mereka kenal sejak kecil, sama orang yang baru mereka temui di kantor atau di kuliahan, bahkan sama orang yang seratus persen asing. Let’s say people you meet on a train. Persetan dengan itu, bahkan kita bisa saling jatuh cinta lewat medsos.”
“Hmm, interesting. Tapi kamu lupa satu hal.”
“Yaitu… ?”
Aku memandang keluar jendela. Tempat sengon dengan daunnya yang jarang bergoyang ditiup angin. “Betul kita jatuh cinta di mana saja, kapan saja, tapi perlu aku ingetin, kita nggak bisa jatuh cinta sama siapa saja.”
Martha sekali lagi menyesap vapenya. Matanya mengerling, tahu kalau ia sudah terpojok. Lalu sambil menaikkan ujung bibirnya yang kuartikan sebagai senyuman (atau seringaian?), ia menjawab, “You sexy little bitch. I can’t stand you this way. Otakmu kalau dikiloin jadi berapa yak?”
Aku mengedikkan bahu acuh tak acuh. “Kamu dari tadi cuma mention tempat-tempat dan waktu kecuali satu, saat kamu bilang kita bisa jatuh cinta sama temen masa kecil kita. Situasi dan tempat itu memang kondisional. Tapi orang enggak, Mar. Kita semua punya tipe. Dan saat tipe itu masuk ke radar kita, masuk dalam jangkauan kita, wajar kalau kita langsung suka meski kita belum ketemu mereka secara langsung.”
“Tipe, berarti hal itu nggak mandang gender dong?”
“Teorinya sih gitu, nggak ngerti kalau di lapangan. Lagian aku straight, jadi agak susah memposisikan diri jadi orang yang ‘menyimpang’,” jelasku sambil membuat tanda kutip dengan jari telunjuk. “Selain tipe, kita juga secara nggak sadar juga menilai kualitas seperti apa yang kita cari dalam diri orang lain kan? Jadi itu juga penentu ketertarikan.”
“Yeah, sure, you are straight as hell. But have you ever wonder if everybody you’ve met, is indeed a little bit gay?”
Aku terkekeh. “Of course not. Menurutku orang yang belok itu karena lingkungannya aja yang mempengaruhi dia. Coba kalau dia nggak bersinggungan sama hal begituan, mereka ya pasti nggak bakal punya pandangan ke sana. Trus aku ngelihatnya LGBTQ itu tren doang. Coba kalau—“
Aku tidak ingat atas apa yang ingin aku sampaikan, selanjutnya Martha menyentuh lenganku lembut yang malah terasa seperti peringatan. Aku berjengit. “What if I’m telling you that I like girl better than a guy and it has nothing to do with that fucking trend.” Martha membuat lingkaran di atas permukaan lengan atasku. Seolah aku ada di sana alih-alih di hadapannya, ia melanjutkan, “Besides, I grow up in such a conservative family. There’s no place for that kinda love.” Ia berbicara padaku dengan suara rendah. Seperti orang tua yang sedang mendisiplinkan anaknya setelah kedapatan berbohong. Seperti seseorang yang terlampau kecewa untuk sekadar marah karena tahu kemarahan tidak ada gunanya untuk menghukum siapapun.
Saat seseorang berada terlalu dekat dengan kita, rasanya udara jadi terlalu pelit untuk dihirup. Ruangan pelan-pelan memudar karena pandangan kita dipenuhi olehnya. Aku bisa menghirup wangi biji kopi yang baru disangrai setiap kali Martha berbicara. Tapi wangi kopinya terlalu manis dan palsu. Juga bisa kutangkap aroma nikotin di sana. Pasti dia menambah kadar nikotin dalam campuran vapenya.
Martha mengangkat jarinya dariku secara tiba-tiba, seolah baru menyadari sesuatu yang penting. Cukup penting agar diri tidak keceplosan atau semacamnya. Lalu ia mendongak. Kalau kami berbicara di ruangan yang sedikit lebih terang dari kamar ini, aku pasti yakin bisa melihat cerminan wajahku sendiri pada bening matanya. “Oh honey… you need a lot to consider,” tutupnya kecut.
Lalu ia menjauhkan dirinya dan kembali merebahkan diri di lantai sambil merokok, seolah aku tidak ada di ruangan itu.
Bekas sentuhannya terasa menyengat. Aku tahu telah salah berbicara dan bahasa tubuh Martha seolah berkata, ‘enyah saja, aku malas denganmu’. Maka dengan langkah kikuk aku meraih kunci mobil dan tasku. Aku meninggalkan ruangan separuh jadi itu tanpa menoleh ke belakang.
Yang aku ingat saat berada di bawah pancuran apartemenku hanyalah… jepit rambut capungku tertinggal dan betapa aku susah menemukan jepitan yang bisa pas di rambutku selain itu. Bahkan saat yang satu patah, aku akan terus memesan model yang sama, ukuran yang sama, ornamen capung yang sama ke pengrajin yang tinggal di Milan itu. Jepit rambutku ketinggalan dan lebih penting lagi, seberapapun kuatnya aku menggosok lenganku dengan sabun, aku masih bisa merasakan sentuhan Martha di sana.
Kami tidak saling bertegur sapa hingga nyaris dua bulan lamanya.
0 notes
Text
Martha and I (Chapter 2)

Saat pertama aku bertemu Martha, dia menyapaku duluan. Bukan, bukan tipikal pertemuan romantis. Dia tidak memberi kesan apa-apa padaku. Hanya mahasiswa baru dengan kucir kuda dan pita yang dipeniti di lengan baju sebelah kiri. Hijau. Dia berarti anggota dari kelompok yang yel-yelnya paling heboh.
“Tumblrmu, itu punyaku,” sapanya sambil menggerak-gerakkan botol air abu-abu di udara.
Saat itu kantin kampus penuh sesak, aku dan teman-temanku duduk di kursi panjang dan nyaris mustahil untuk tidak saling sikut.
“Hm?” Aku melihat botol di tanganku, tidak ada bedanya dengan yang perempuan itu pegang.
Seperti bisa membaca kebingunganku, dia menghela napas. “Tumblrku masih sisa separuh. Sedang yang ini sudah kosong.”
Aku tertawa canggung. “Eh, sorry-sorry.”
Dia hanya mengangguk, kembali menekuri sotonya. Aku berlalu mengejar teman-temanku yang sudah memanggilku dari tadi. Dua minggu kemudian kami duduk bersebelahan di kelas Pengantar Statistik Sosial. Dua minggunya lagi kami memilih untuk menjadi satu kelompok dalam matkul lainnya. Dua bulan kemudian aku tidak bisa ke mana-mana tanpa Martha di sisiku.
***
“What do you think about asexual?”
“A… apa? aseksual?” tanyaku.
Sore yang cerah. Mahasiswa pergi ‘merumput’. Kami akan menggelar alas di bawah naungan pohon yang melingkari lapangan samping kampus. Lapangan rumput ini biasa digunakan untuk organisasi ekstra seperti marching band, panahan, pencak silat (yah, kami punya ekstra untuk kegiatan satu itu) atau apapun yang membutuhkan lahan luas. Kata Martha, jenis pohon itu akasia. Tapi karena penampakannya yang kuno dan dahannya yang seolah terus menggapai bagian bolong di tengah lapangan, pohon-pohon itu lebih tampak seperti beringin di mataku.
“Berhentilah berbicara hal-hal aneh padaku. Aseksual. Bah,” selaku.
Dia menggulung jaketnya kemudian menjadikan buntelan itu sebagai tatakan laptop. “Ayolah, nggak usah cosplay jadi orang bego. Nggak cocok.”
“Asexual sounds odd to me. Is it someone who identify themselves as the one who didn’t enjoy having sex?”
“Hampir bener. Kalau aku lurusin jadi gini, mereka nggak tertarik sama apapun yang merujuk ke sana—“
“Even role-play?” tanyaku.
“Yep, even role-play. Or maybe kissing too.”
Aku tertawa, “How about hugging?”
“Mungkin masuk hitungan juga.”
“Ugh, boring. Nggak ada yang bisa tahan tanpa kontak fisik. Apalagi sama-sama suka.” Memangnya kenapa ada larangan berduaan karena yang ketiga setan kalau bukan karena hal seperti ‘itu’ sangat sulit ditolak.
“Gimana kalau dibalik, nggak ada yang bisa tahan digrepe-grepe terus?”
“Tapi kan kalau sama-sama ada concern ya nggak apa-apa, dong.”
“Coba kamu perhatiin lagi omonganmu. You said that ‘sama-sama’, gimana kalau pihak satunya nggak mau? Lagian bukan itu yang mau aku bahas. Dasar,” katanya sambil menimpuki kepalaku pelan dengan map yang barusan ia keluarkan.
Aku terdiam. Suara hentakan kaki dari laki-laki yang barusan jogging di paving di belakangku terdengar nyaring. Oh, dia akan kebas setelah lari kecilnya itu.
Langit benar-benar jernih, mengingatkanku pada kolam renang yang terlalu banyak kaporit. Ada ya orang yang sebegitu tidak maunya disentuh? Aku suka semua sentuhan. Aku tidak bisa menahan diriku untuk tidak begitu. Sepertinya itu sudah jadi salah satu love language-ku. Apalagi pelukan. Memang siapa yang tidak suka dipeluk? Kata mama, saat orang sedih atau senang, pelukan bisa dipakai untuk dua kondisi itu. Kenyamanan seperti apa yang bisa mengimbangi kontak fisik semacam itu. Saat aku semakin dewasa, aku menjadi tambah mengerti kalau pelukan bukan hanya soal mentransfer rasa nyaman tapi juga keintiman. Yah, asalkan yang dipeluk atau yang memeluk juga sadar dengan kebersihan diri. Semuanya oke. Berhubung aku tidak punya masalah dengan bau badan, barangkali karena itu kepercayaan diriku untuk memeluk tidak pernah turun.
“Bayangin kamu tertarik sama seseorang, tapi nggak punya pikiran ke sana. Secara seksual,” lanjutnya.
“Becanda ah, masa ada orang begitu.”
“Sayang sekali mereka ada. Nggak semua orang dibesarkan dalam keluarga yang kayak kamu, Na.”
Betul, tidak semuanya tumbuh dalam keluarga yang tidak jaim dan gampang mengobral afeksi. Dan coba tebak, sepertinya aku tahu Martha ingin menggiringku ke mana. “Oke, go on.”
“Setahuku aseksual ada dua, aromantik dan romantik. Mereka tetep bisa suka sama orang, mereka normal tapi bukan tipikal normal yang selama ini kita tahu. Aro atau aromantik, artinya dia nggak tertarik secara seksual maupun romantik, ini juga biasa disambung jadi satu istilah, AroAce. Satunya lagi aseksual yang masih ada ketertarikan romantik.”
Dia terlihat cerdas, seperti biasanya. Aku tidak heran kalau 10 tahun dari sekarang dia akan mengajar di kelas-kelas atau bahkan seminar-seminar besar. “Wait, let me make this clear, apalagi yang AroAce. Jadi misal, misal nih ya, kamu aseksual dan aromantik, trus katakanlah kamu tertarik ke orang... tapi karena apa?” Aku tidak bisa menahan untuk tidak tertawa geli. Betapapun aku ingin menjaga perasaan Martha, karena kalau dilihat dari air mukanya yang serius, topik ini cukup penting baginya. “Oke maaf, bisa tolong lanjutkan.” Ya, Tuhan aku harus belajar untuk tidak tertawa terus.
Martha menghela napas gemas. “Gini deh, kamu selama ini memaknai romantis dan seksual itu seperti apa?”
“Aku…” well, aku tidak suka saat Martha menggunakan kepintarannya untuk menyerangku—meski ia tidak berniat begitu. Tapi aku merasa dia seperti itu. “Aku pikir keduanya nggak bisa dipisahin deh. Kan emang sewajarnya orang yang tertarik itu karena kebutuhan seksual dan romansa. And that’s two kinda things that we looking for in relationship, isn’t?”
“Nyaris betul, tapi kalau boleh ngoreksi, hasrat seksual itu karena kebutuhan biologis, kalau romansa atau romantis itu lebih kepada kebutuhan untuk memiliki ikatan. See? Tampak sama tapi beda.”
Sinar matahari jadi merah jambu. Beberapa mahasiswa yang baru selesai kuliah umum keluar dari gedung D. Aku membuka kotak nasi yang isinya bukan nasi—aku membawa beberapa buah anggur dan buah pir yang sudah dipotong dadu. Awalnya kami memutuskan piknik di tempat ini untuk kerja kelompok, tapi masalah AroAce ini sepertinya lebih menarik untuk dibahas.
“So… are you?” todongku.
Ia mendongak dari layar, memberikan tatapan pura-pura bingungnya. “Aku kenapa?”
“Are you AroAce?” tanyaku nakal. Dia membalasnya dengan kerutan kecil di alisnya yang rapi. Kerutan yang berarti tidak setuju yang pura-pura. Martha hanya menggeleng tak habis pikir dan kembali menunduk. Kugunakan momen itu untuk menyerangnya dengan gelitikan. Seperti biasa, dia kaget bukan main. Semula dia tertawa dan kami hampir mengacak-ngacak lapangan rumput yang sebenarnya sudah acak-adut. Ada jeda, kubiarkan ia menyelesaikan tawanya dan mengambil napas. Saat seranganku yang kedua, Martha kembali menjadi Martha yang tidak suka disentuh.
“Please don’t do that again. I. Insist. I don’t like it, Na.” Nada suaranya tegas dan berjarak. Martha lagi-lagi dengan keseriusannya. Tidak seperti teman-temanku yang pasti membalas apa yang barusan kulakukan pada Martha, gadis ini jelas merasa terganggu meski tadi dia tertawa. Lalu ia mendiamkanku seolah aku sarang laba-laba. Terkadang sifatnya yang seperti ini membuatku terluka dengan cara yang tidak bisa kumengerti. Aku merasa tidak diterima. Dan sebaliknya, pasti dia merasa bahwa sikapku yang seringnya tidak terduga sangat sukar diterima. Aku rasa kami impas.
Satu per satu gerombolan yang sedang berpiknik mengemas alas mereka. aku menekuri cetakan materi sambil sesekali membahas hal-hal penting. Selebihnya kami diam. Martha sibuk mengetikkan apalah itu yang menurutku daripada kerja kelompok ini lebih cocok disebut Kerja Martha. Dia nyaris tidak mengizinkanku berkontribusi.
Saat kukatakan sebentar lagi maghrib, dia setuju untuk bangkit dan menyudahi Kerja Martha. Memang suasana selalu bisa cair setelah keadaan membisu seperti tadi. Dia membantuku bangkit dan menggamit lenganku. Sepanjang perjalanan pulang, kami mirip anak kembar yang tidak mau lepas. Benarkah ia tidak suka disentuh? Mengapa keseringan aku mendapati sebaliknya.
Percakapan AroAce itu membuatku banyak berpikir. Oh ya, ngomong-ngomong, aku belum jatuh cinta pada orang aneh ini. Selanjutnya aku bahkan tidak tahu bisa sesayang itu terhadap manusia. Pada masa-masa awal berteman, aku hanya tertarik dan penasaran dengan kerpibadiannya. Hanya itu. Hingga sesuatu mengubah segalanya.
Sesuatu yang membuatku tidak pernah memandang Martha dengan sama lagi.
5 notes
·
View notes
Text
Martha and I (Chapter 1)

“Tapi aku nggak bisa komitmen, di situ masalahku.” Dia memutar-mutar jarinya di atas meja, seperti menggambar tempat yang tidak pernah ia izinkan siapapun untuk memasukinya. Aku tahu dia ingin melarikan diri dari percakapan seperti ini.
“Kamu belum nemu aja orang yang pas. Yang bikin kamu bahkan lupa sama ketakutanmu,” ujarku sambil lalu.
“Meskipun ada, aku tetep nggak bisa. Nggak mau lebih tepatnya. Aku benci terikat.”
Oh, lihat makhluk keras kepala ini. “Kamu lucu banget, trus pacarmu itu kamu kemanain? Katanya nggak bisa terikat.”
Dia melirikku, memperingati. “Dia beda, lagian kami LDR. Yang kita omongin sekarang kan kemungkinan semisal ada orang dalam jangkauanku, orangnya real, dan dia jelas-jelas ngajakin buat memulai hubungan. Di situ posisinya beda sama aku dan pacarku yang yah… kamu ngerti sendirilah gimana.”
Aku diam sebab aku paham. Martha dan pacarnya bertemu melalui akun RP di Twitter. Dunia yang sungguh absurd bagiku. Mereka sudah tiga tahun bersama. Mungkin pernah bertemu, mungkin juga tidak. Dia tidak pernah bercerita detail hubungannya.
Dia mengganti topik dengan hal lain yang tidak kuingat lagi tentang apa.
Namanya Martha, dia sekepala lebih tinggi dari padaku. Tidak suka disentuh, tidak suka kucing, tidak suka keramaian, tidak pandai bergaul, tidak tahu caranya bermanis tutur, tidak suka sayur. Kulitnya lebih pucat dari punyaku. Sering menyetel lagu-lagu yang membuatku sakit kepala. Perangainya angin-anginan dan paling anti dengan orang manja. Namanya Martha, warna rambutnya cokelat tua dan keriting. Wangi tubuhnya mengingatkanku pada lotion beraroma kelapa muda, lembut tapi kelembutan yang dewasa. Dia punya hubungan yang rumit dengan ibunya dan aku menangkap kesan dia tidak suka dengan sikapku yang seperti ibu-ibu. Yang mengatur meski karena kasih sayang.
Martha yang rumit, kadang dia menatapku seperti ingin menciumku. Tapi tidak bisa. Tidak boleh. Kami sahabat dan dia punya pacar. Lagipula kami tinggal di negara yang tidak memberi tempat bagi cinta semacam ini.
6 notes
·
View notes
Text
Saat Kamu Dewasa dan Jatuh Cinta
Ini yang kemudian aku pelajari: (1) kalau kamu nggak belajar mencintai dirimu sendiri terlebih dulu, cinta sebanyak apa pun dari orang lain tidak akan pernah cukup, (2) nggak ada yang namanya pasangan sempurna. Saat memilih seseorang, kamu juga memilih cacat dan hantu dalam dirinya, (3) sudahi kalau memang semuanya nggak bisa diperjuangin lagi. Kamu berhak bebas, begitu pula dia juga berhak dapat kejelasan, (4) semuanya jadi penuh jebakan, bahkan kamu bisa mengira sedang jatuh cinta padahal cuma kesepian saja, (5) belajar untuk berhenti membuat skenario palsu dalam kepalamu, supaya rasa sakit karena nggak bisa memiliki bisa sedikit dijinakkan, (6) kamu mulai mempertanyakan moralmu saat ternyata cintamu jatuh kepada orang yang telah memiliki pasangan, seseorang yang tampak sempurna bagimu tapi sayang dia sesama jenis, dan 1001 jebakan yang membuatmu ingin mati rasa saja, (7) realistis sangat membantu untuk lekas sembuh dari patah hati dan alegori jatuh cinta. Dan seperti kebanyakan hal baik di dunia ini yang nggak bisa instan, begitupula menjadi realistis. Pahami bahwa prosesnya hanya akan berhasil kalau kamu berani untuk bersabar, (8) kamu nggak bisa memaksakan komitmen terhadap seseorang. Meski dia menyukaimu, belum tentu dia mau menjalin hubungan denganmu, (9) atasi dulu luka dalam dirimu. Kalau luka itu berasal dari orang lain, rawat dulu baik-baik. Usahakan nggak tergantung sama kebaikan orang lain, mencari pelarian misalnya, (10) nggak ada yang permanen apalagi perasaan. Badai yang hebat saat kamu jatuh cinta pada seseorang, pasti akan reda juga. Waktu akan membantumu untuk lupa.
–lunarmaiar, 2021
5 notes
·
View notes